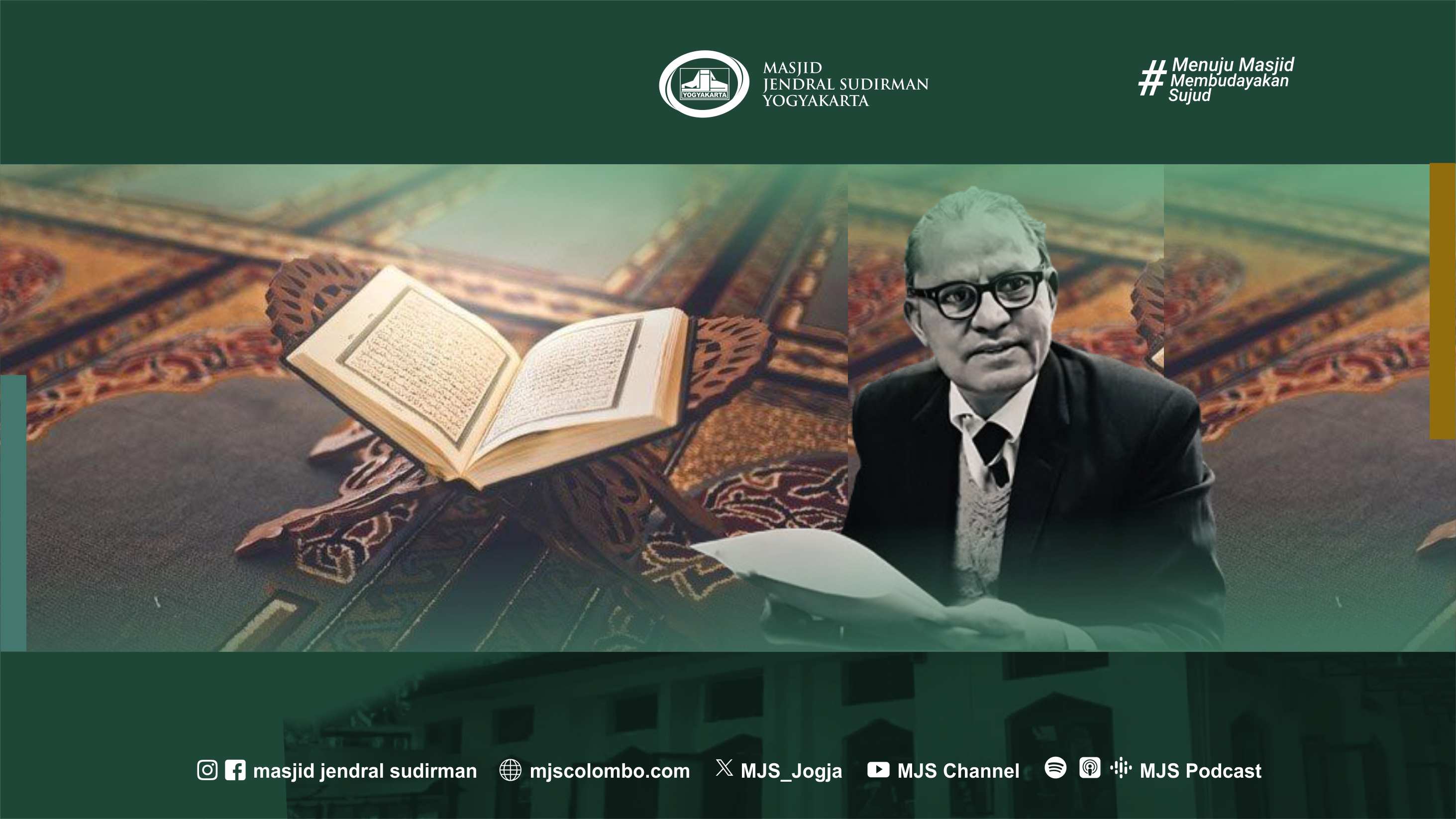Fazlur Rahman dan Pendekatan Humanis terhadap Ajaran Islam
Di tengah dinamika masyarakat modern, umat Islam menghadapi tantangan yang kompleks. Perdebatan interpretasi agama, konservatisme ekstrem, hingga ketimpangan sosial menuntut pemikiran Islam yang lebih rasional, kontekstual, dan etis. Dalam konteks ini, cendekiawan Islam modern asal Pakistan hadir dengan pendekatan humanis terhadap Al-Qur’an dan ajaran Islam. Pemikirannya menekankan bahwa Islam bukan sekadar ritual formal atau dogma literal, tetapi sistem moral dan etika yang harus dipahami dalam konteks sosial, sejarah, dan tujuan universal agama.
Fazlur Rahman lahir pada 1919 di Pakistan, ia menempuh pendidikan hingga menjadi profesor di University of Chicago. Dikenal melalui karya besar seperti Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982), Islam (1979), dan Major Themes of the Qur’an (1980), pemikir ini menekankan pentingnya memahami Al-Qur’an secara kontekstual dan rasional (Nurdiansyah, 2025).
Menurut Rahman, Al-Qur’an adalah kitab petunjuk yang relevan sepanjang zaman, tetapi pemahamannya harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan sejarah saat wahyu diturunkan. Dengan pendekatan ini, kitab suci menjadi panduan moral yang fleksibel dan aplikatif bagi kehidupan modern.
Pemikiran ini dibangun atas fondasi klasik dan modern. Dari tradisi Islam klasik, Imam Al-Ghazali memengaruhi dalam menekankan integrasi moral, akal, dan iman sebagai dasar etika Islam, sementara Ibn Rushd (Averroes) memberi pengaruh pada harmonisasi antara akal dan wahyu. Selain itu, pemikiran Barat juga memberi pengaruh penting: John Dewey memengaruhi konsep pendidikan progresif yang membebaskan berpikir kritis, sedangkan Wilhelm von Humboldt memberi inspirasi terkait kebebasan individu dan pendidikan integral. Kombinasi pengaruh ini membentuk perspektif unik: Islam yang rasional, humanis, dan relevan dengan kehidupan modern.
Salah satu gagasan utama Rahman adalah tafsir kontekstual Al-Qur’an. Setiap ayat harus dipahami dalam kerangka tujuan moral dan sosialnya (Nurdiansyah, 2025). Pendekatan ini menolak tafsir literal yang kaku dan membuka ruang bagi pemikiran Islam yang dinamis. Misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sosial dan ekonomi harus dilihat dalam konteks moral dan historis, sehingga pemahaman agama dapat diaplikasikan secara relevan dengan kehidupan kontemporer.
Selain itu, etika menjadi inti ajaran Islam, yang menjadi dasar setiap tindakan umat (Maraimbang, Harahap, & Drajat, 2019). Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diinternalisasi dalam praktik sosial, politik, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, agama tidak hanya menjadi ritual formal, tetapi juga pedoman moral yang nyata dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.
Gagasan penting lainnya adalah pendidikan yang membebaskan. Ia menekankan pendidikan yang mendorong pemikiran kritis, rasional, dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama (Fathonah, 2019). Pendidikan bukan sekadar menghafal teks atau ritual, tetapi mengembangkan kemampuan intelektual dan moral individu. Generasi muda yang dididik dengan prinsip ini mampu memahami Islam secara relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai spiritualnya, sekaligus siap berperan aktif dalam masyarakat modern.
Pemikir ini juga menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam harus mendukung hak individu, dialog antaragama, dan kerangka demokrasi yang menghormati kebebasan serta hak-hak manusia. Prinsip ini sangat relevan bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia, karena mendorong umat melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman, dan mengurangi potensi konflik akibat tafsir literal atau dogmatis.
Pemikiran ini memiliki implikasi praktis dalam kebijakan sosial dan pendidikan Islam. Kurikulum sekolah dan universitas Islam dapat mengadopsi prinsip tafsir kontekstual, etika, dan rasionalitas (Fathonah, 2019). Misalnya, pembelajaran Al-Qur’an bisa disertai konteks historis dan sosial agar siswa memahami tujuan moral di balik ayat-ayat tertentu. Aktivitas dakwah pun dapat menekankan aspek etika dan moral, bukan sekadar dogma literal, sehingga umat mampu mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara relevan dan humanis.
Selain itu, pemikiran ini menyoroti isu ekstremisme agama. Ekstremisme muncul dari pemahaman literal dan kaku terhadap teks agama. Dengan memahami konteks dan tujuan moral wahyu, umat Islam dapat membangun masyarakat inklusif, toleran, dan adil. Isu-isu sosial seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi gender, dan hak minoritas dapat diatasi dengan pendekatan etis, sehingga Islam menjadi kekuatan moral dan sosial yang positif.
Lebih jauh, Rahman menekankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Konservatisme ekstrem yang menolak perubahan zaman ditolak, namun modernitas tidak harus menghapus nilai spiritual dan moral. Umat Islam dapat berpikir kritis, mengadopsi ilmu pengetahuan modern, dan membangun masyarakat demokratis tanpa kehilangan identitas agama. Pendekatan ini relevan bagi generasi muda yang hidup di era digital dan globalisasi, di mana tantangan moral dan sosial semakin kompleks.
Pemikiran ini juga relevan dalam era digital dan globalisasi, di mana informasi agama tersebar cepat melalui media sosial. Tafsir kontekstual dan etika menjadi penting agar umat tidak terjebak pada informasi dangkal atau disinformasi yang memicu ekstremisme dan konflik sosial. Konten agama yang viral perlu dipahami secara kritis, sehingga pemahaman Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, prinsip pendidikan membebaskan dapat diterapkan pada literasi digital dan kritis. Pendidikan yang menekankan akal, etika, dan konteks sosial membekali generasi muda untuk menilai informasi, berdialog antaragama, dan membuat keputusan moral yang tepat. Pendekatan ini membantu membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan beradab, di mana agama berfungsi sebagai panduan moral, bukan alat memecah belah.
Pemikiran ini juga menawarkan solusi untuk kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Nilai etika Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harus menjadi dasar kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan prinsip ini, Islam dapat menjadi sumber inspirasi pembangunan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat dilakukan di bidang pendidikan, kebijakan sosial, dan aktivitas dakwah yang menekankan moral dan etika, bukan dogma literal.
Secara keseluruhan, pendekatan humanis ini menawarkan panduan praktis dan relevan bagi umat Islam modern. Agama dan akal dapat berjalan beriringan, sehingga umat dapat menghadapi tantangan global, digital, dan sosial dengan bijak. Mengadopsi gagasan ini berarti menghadirkan Islam yang membebaskan, humanis, dan relevan, sekaligus memperkuat identitas spiritual dalam masyarakat yang terus berubah.
Pendekatan humanis terhadap Al-Qur’an, etika, pendidikan yang membebaskan, demokrasi, dan pluralisme yang menawarkan panduan praktis untuk membangun masyarakat toleran, demokratis, dan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menghidupkan Islam yang membebaskan, relevan dengan zaman, dan mampu menjadi inspirasi moral bagi seluruh umat manusia.
Dengan meneladani pendekatan humanis ini, umat Islam modern di Indonesia dan dunia dapat menghadapi tantangan kontemporer secara bijaksana, mengintegrasikan iman dengan rasionalitas, serta membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Warisan intelektual ini tidak hanya relevan untuk akademisi, tetapi juga untuk setiap individu yang ingin menjalani kehidupan dengan integritas moral dan kesadaran sosial, sekaligus menjaga identitas spiritual dalam masyarakat yang terus berubah.
Category : keislaman
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial